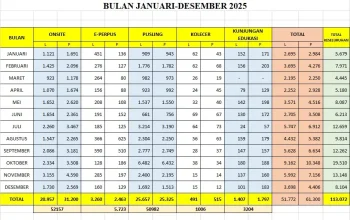JAKARTA dan Bandung dikenal sebagai kota yang tak pernah kehabisan air, setidaknya dalam urusan hujan, banjir, dan keluhan warga. Namun ada satu hal yang justru mengering di dua kota ini, mata manusia.
Fakta menyebutkan, prevalensi mata kering mencapai 41 persen. Angka yang cukup untuk membentuk satu redaksi penuh, lengkap dengan kopi dingin, tenggat waktu, dan keluhan yang sama, mata perih tapi merasa baik baik saja.
Ironisnya, banyak dari mereka yang matanya kering justru tidak menyadarinya. Barangkali karena sudah terlalu lama berdamai dengan rasa sepet. Atau karena merasa perih adalah bagian dari dedikasi. Di dunia jurnalistik, keluhan semacam itu sering dianggap aksesori kerja, selevel dengan tas ransel, kartu pers, dan laptop yang baterainya tak pernah penuh.
Cobalah intip rutinitas jurnalis. Pagi dimulai dengan memindai pesan redaktur, siang beradu argumen dengan narasumber, sore mengejar kutipan, malam menatap layar hingga mata terasa seperti arsip lama, berdebu, rapuh, tapi dipaksa tetap terbuka. Di sela sela itu, jurnalis menatap layar ponsel, kamera, laptop, semuanya bercahaya, semuanya menuntut fokus. Kedipan mata terlupakan. Air mata tidak ada di anggaran.
Di lapangan, situasinya lebih dramatis. Asap knalpot, debu proyek, dan panas kota bersatu padu menguji ketahanan kornea. Jurnalis berdiri berjam jam di bawah terik, menunggu pernyataan yang sering kali tak kunjung datang. Ketika akhirnya datang, ia mencatat dengan mata yang mulai protes, tapi tetap diam. Karena mengeluh dianggap tidak produktif.
Barangkali di sinilah letak persoalannya. Kita terbiasa merawat alat kerja yang terlihat—kamera dibersihkan, ponsel diisi daya, laptop dilindungi. Tapi mata, yang bekerja tanpa suara dan tanpa notifikasi, justru dilupakan. Padahal, menjaga mata tetap nyaman bukan soal kemewahan, melainkan soal keberlanjutan kerja.
Kesadaran sederhana, seperti memberi waktu istirahat pada mata, mengurangi paparan layar tanpa jeda, atau memastikan mata tetap terhidrasi—sering dianggap sepele. Padahal dari kebiasaan kecil itulah kualitas penglihatan, konsentrasi, dan bahkan ketepatan membaca fakta ditentukan.
Mata kering adalah peringatan sunyi dari tubuh di tengah hiruk pikuk kota. Ia tidak meminta headline, tidak butuh liputan khusus. Ia hanya mengingatkan bahwa kerja intelektual tetap membutuhkan kondisi fisik yang dijaga. Jurnalisme yang tajam berangkat dari pandangan yang jernih—dan kejernihan, seperti kebenaran, perlu dirawat, bukan diasumsikan selalu ada.
Yang menarik, mata kering jarang masuk liputan. Tidak ada konferensi pers soal ini. Tidak ada breaking news bertajuk “Kornea Darurat”. Padahal dampaknya nyata, pandangan kabur, perih, cepat lelah. Namun karena gejalanya halus, ia disamarkan oleh istilah favorit dunia kerja, nanti juga biasa.
Mungkin ini sebabnya mata kering menjadi epidemi sunyi. Ia tidak berisik seperti sirene ambulans, tidak viral seperti skandal politik. Ia hadir perlahan, mengeringkan hari demi hari, hingga orang mengira rasa perih adalah pengaturan bawaan kehidupan kota. Terlebih bagi jurnalis, yang terbiasa menatap kenyataan keras, bahkan ketika matanya meminta jeda.
Di titik inilah kampanye SePeLe mulai relevan. Bukan sebagai jargon medis, melainkan sebagai pengingat. Bahwa mata perih, sepet, dan lelah bukan perkara sepele. Bahwa rasa tidak nyaman yang terus ditoleransi justru menumpuk menjadi masalah. SePeLe mengajak orang berhenti sejenak, menyadari sinyal kecil dari mata, dan mengakui bahwa mata juga punya batas.
Pada akhirnya, mata kering adalah metafora yang pas untuk kerja jurnalistik di kota besar, terus menyerap, jarang disegarkan. Kita menuntut mata untuk melihat fakta dengan jernih, sementara lupa memberinya hak paling dasar, istirahat dan pelumas. Maka jangan heran jika di kota yang basah oleh hujan, justru mata manusianya kekurangan air.
Barangkali sudah saatnya ruang redaksi mengakui satu hal sederhana, mata juga pekerja. Ia punya batas, ia butuh perhatian. Sebab tanpa mata yang sehat, berita sehebat apa pun hanya akan terlihat samar, dan fakta, seperti mata, tak seharusnya dibiarkan kering.(*)